KORUPSI, KEJAHATAN BERGENGSI?
Oleh : Tata Danamihardja
Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada ibu, ada ayah.
Ada muda, ada tua. Ada gelap, ada terang. Ada positif, ada negatif. Ada
baik, ada jahat. Selalu begitu. Semua pasti ada maksudnya, walau kita
sering tidak mengerti, tidak paham, apa makna di balik semua itu. Dan kita
memang tidak perlu berkutat mencari tahu, karena yang lebih penting adalah
memilih sisi positif dari pasangan-pasangan sifat maupun keadaan yang
diciptakan Tuhan. Itu sebabnya kita dibekali software super canggih yang
namanya akal, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah
mampu membedakan, kita juga dituntut untuk memilih. Dalam proses memilih
ini, selain menggunakan akal, diperlukan juga perangkat lain yang namanya
nurani, yang kadang disebut juga dengan istilah hati kecil. Orang bijak
mengatakan, hati kecil merupakan satu-satunya bagian dari diri manusia
yang tidak pernah berbohong, sehingga memiliki peran besar dalam
menentukan kualitas moral seseorang.
Idealnya memang begitu. Dalam setiap tindakan, kita selalu dituntut untuk
menggunakan dua perangkat tadi, akal dan nurani. Namun sejalan dengan
semakin tuanya umur dunia, justru peran kedua alat canggih itu semakin
terpinggirkan. Tuntutan hidup yang semakin mengedepankan semangat
hedonisme, membuat akal dan nurani justru dianggap sebagai penghambat.
Pilihannya bukan lagi mempertimbangkan mana yang terbaik, melainkan mana
yang paling menguntungkan. Makanya tidak heran jika kejahatan semakin
merajalela, seperti sering terungkap lewat berbagai media. Pencurian,
perkosaan, pembunuhan, penyuapan, sampai korupsi, menjadi menu harian
dalam pemberitaan koran, radio mau pun TV. Menurut berbagai lembaga
survey, informasi-informasi seperti ini bahkan mampu menaikkan rating
acara TV/radio serta oplah media cetak, yang pada gilirannya mampu
mendongkrak pemasukan iklan.
Yang menarik adalah, bila kita amati, secara umum ternyata ada kelas-kelas
yang membedakan perlakuan sosial masyarakat, termasuk piranti/aparat
hukum, terhadap berbagai jenis kejahatan yang ada. Tengoklah
maling-maling kelas teri yang ditahan di kantor polisi. Mereka sudah babak
belur bahkan sebelum mereka diputuskan bersalah atau tidak oleh
pengadilan. Muka bengkak, bibir jeding, tubuh penuh luka bekas sundutan
rokok. Sudah bukan rahasia bahwa polisi masih sulit meninggalkan hobi
mereka untuk menyiksa para tersangka kejahatan kelas teri ini, hanya untuk
mendapatkan pengakuan yang sesuai dengan keinginan mereka. Belum lagi
sebagian anggota masyarakat yang seringkali -diminta atau tidak- juga ikut
menyumbang pukulan dan tendangan. Sekarang tengok para tersangka korupsi,
yang belakangan jumlahnya meningkat gila-gilaan. Mereka yang rata-rata
datang dari kelas menengah atas ini, aman dari perlakuan tidak
menyenangkan. Apalagi hampir bisa dipastikan bahwa mereka punya pengacara
yang siap membela jika terjadi apa-apa terhadap mereka. Polisi berpikir
seribu kali untuk melakukan kekerasan fisik terhadap mereka, kecuali siap
menuai masalah. Masyarakat juga tidak berani bersikap tidak sopan, apalagi
bertindak kasar. Inilah fakta yang tidak bisa dipungkiri.
Apa gerangan penyebab perbedaan perlakuan ini? Agak sulit memang untuk
mencari jawabannya, terutama jika ditinjau dari sudut logika, meskipun
keduanya sama-sama tersangka pelaku kejahatan. Padahal sesungguhnya yang
membedakan hanyalah pembagian kelas kejahatan menurut standar barat.
Mereka yang berisiko mendapat perlakuan kekerasan fisik adalah tersangka
pelaku kejahatan kerah biru (blue collar crime), yakni mereka yang di
dalam tatanan masyarakat dianggap sebagai kelas buruh, kelas orang biasa,
kelas the man on the street. Sementara para tersangka kasus korupsi
digolongkan dalam tersangka kejahatan kerah putih (white collar crime).
Mereka ini memang memiliki status sosial yang cukup baik di masyarakat,
serta tentunya memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Kaum elit,
begitu istilah awam menyebut mereka.
Koruptor memang maling berkelas. Saking berkelasnya, masyarakat, bahkan
media, cenderung lebih hati-hati memperlakukan mereka. Istilah-istilah
yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan mereka menunjukkan hal itu.
Istilah pelaku penggelapan, misalnya, lebih disukai ketimbang istilah
garong. Penyalahgunaan dana dipakai untuk mengganti kata korupsi. Padahal
esensinya sama saja, mencuri. Koruptor bahkan memiliki kadar kejahatan
yang jauh lebih besar dibanding pencuri kelas teri. Logikanya, mana ada
orang korupsi hanya untuk beli beras buat makan hari ini. Kalau pun ada,
mungkin berasnya ratusan ton.
Perlakuan masyarakat juga tidak jauh berbeda. Sanksi moral untuk koruptor
cenderung lebih ringan dibanding sanksi moral terhadap maling ayam. Orang
masih bisa membungkuk hormat di hadapan orang yang sudah nyata-nyata
diputus pengadilan sebagai koruptor. Sementara, maling ayam yang mencuri
untuk sekedar bisa mengganjal perut, dikucilkan tanpa ampun.
Inilah realita yang ada di sekitar kita. Korupsi, seolah-olah kanker ganas
yang amat sangat sulit untuk disembuhkan. Dari tingkat atas sampai tingkat
bawah, selalu terjadi. Celakanya, di tengah masyarakat yang menganut
budaya patron, budaya panutan, justru banyak sekali orang-orang yang
seharusnya menjadi teladan, malah menjadi pelaku kejahatan kerah putih
ini. Akibatnya, semakin lama orang semakin menganggap bahwa korupsi
merupakan hal yang wajar dilakukan oleh para petinggi, dan itu yang
akhirnya dicontoh oleh orang-orang yang ada dibawahnya. Maka berurat
akarlah korupsi, dari atas sampai ke bawah, dari yang berskala nasional,
regional, sampai tingkat lokal. Belakangan kita dikejutkan oleh maraknya
kasus korupsi yang terjadi di belasan DPRD Tingkat II. Wakil rakyat yang
seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, malah merampok uang rakyat.
Sebuah kekejian dan pengkhianatan yang sungguh menyakitkan.
Belakangan, korupsi malah cenderung dianggap sebagai perbuatan terhormat.
Rasanya kurang pas kalau ada kesempatan, tapi tidak melakukan korupsi.
Selain bisa menunjang semangat memuja kebendaan, korupsi juga bisa
menaikkan popularitas, yang dalam skala tertentu bisa membantu mencapai
tujuan-tujuan politis maupun tujuan-tujuan lainnya. Bahkan kalau berhasil
lolos dari jeratan hukum, terkesan ada semacam kebanggaan bahwa diri sang
pelaku memiliki kehebatan luar biasa, kekebalan hukum, sekaligus ?
barangkali- ketebalan muka di atas rata-rata, sehingga membuat yang
bersangkutan semakin menepuk dada.
Lalu apa yang bisa dilakukan oleh kita, untuk menyikapi semua itu? Ajaran
Islam mengatakan, jika melihat kemunkaran ada tiga hal yang harus
dilakukan. Pertama, jika memiliki kekuatan, lawanlah kemunkaran dengan
tangan. Artinya, kalau kebetulan anda menjadi hakim yang punya kewenangan
memutus perkara korupsi, maka jatuhkanlah keputusan yang adil. Kalau anda
jadi polisi, perlakukanlah semua orang dengan adil, jangan pilih-pilih
berdasarkan pertimbangan uang atau status sosial. Kalau anda jadi
Presiden, jangan cuma memanjakan konglomerat, tapi perhatikan juga rakyat
kecil. Kedua, jika tidak bisa dengan tangan, lakukanlah dengan lisan.
Ungkapkanlah kebenaran, jangan ditutup-tutupi. Sebutlah warna hitam dengan
Hitam, dan warna putih dengan Putih, jangan ditukar-tukar. Ketiga, jika
dengan lisan juga masih tidak mampu, maka lawanlah dengan hati. Jangan
pernah merestui kemunkaran, meskipun -kata Nabi- inilah selemah-lemahnya
iman. Semua itu bisa kita lakukan dengan berpedoman pada akal sehat dan
hati nurani.
Yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan pemahaman agama dan
pemahaman moral yang baik kepada anak-anak kita sejak dini. Jangan sampai
pemahaman salah kaprah tentang mana yang baik mana jelek, mana benar mana
salah, berlangsung terus menerus hingga menjadi kebenaran itu sendiri.
Selain itu, jadikan diri kita sebagai panutan yang baik buat anak-anak
kita. Jangan melarang anak-anak merokok sambil mulut kita mengepulkan asap
rokok. Artinya, jangan mengajarkan untuk tidak korupsi, padahal kita
sendiri koruptor. Rantai kebejatan moral harus diputus, dan itu harga
mati. Kecuali, jika kita ingin anak-anak kita, generasi mendatang, menjadi
pelaku-pelaku korupsi kelas kakap karena mereka menganggap koruptor
merupakan profesi bergengsi. Na?udzubillah.
**Tulisan ini pernah dimuat di http://www.sarikata.com




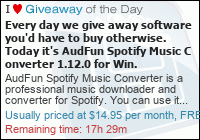
0 Comments:
Post a Comment
<< Home